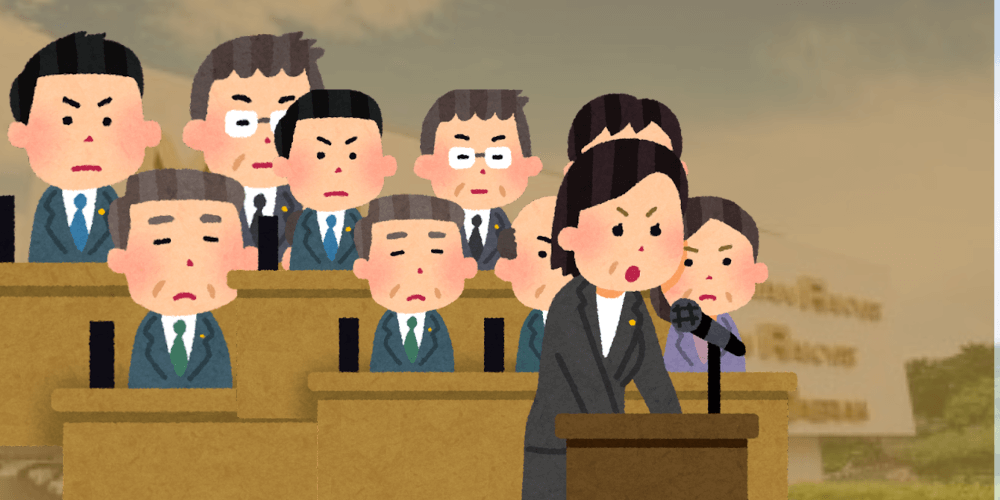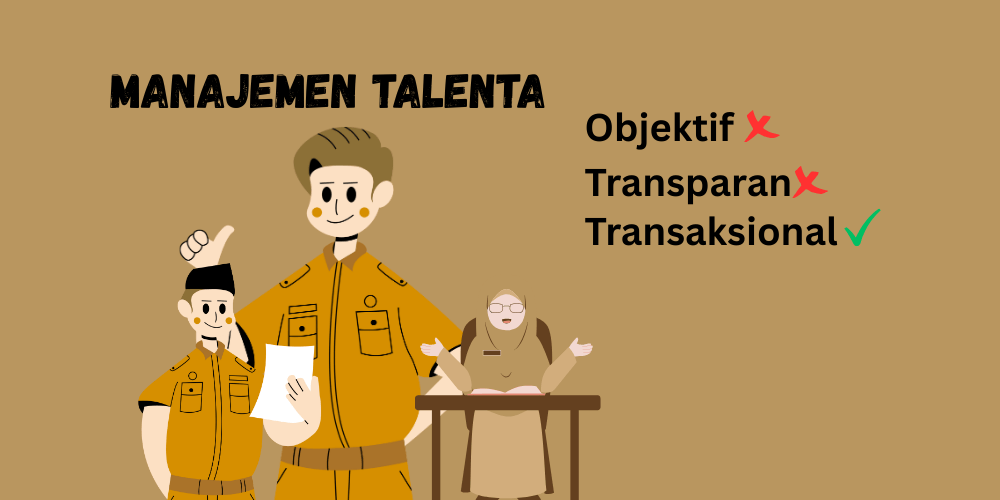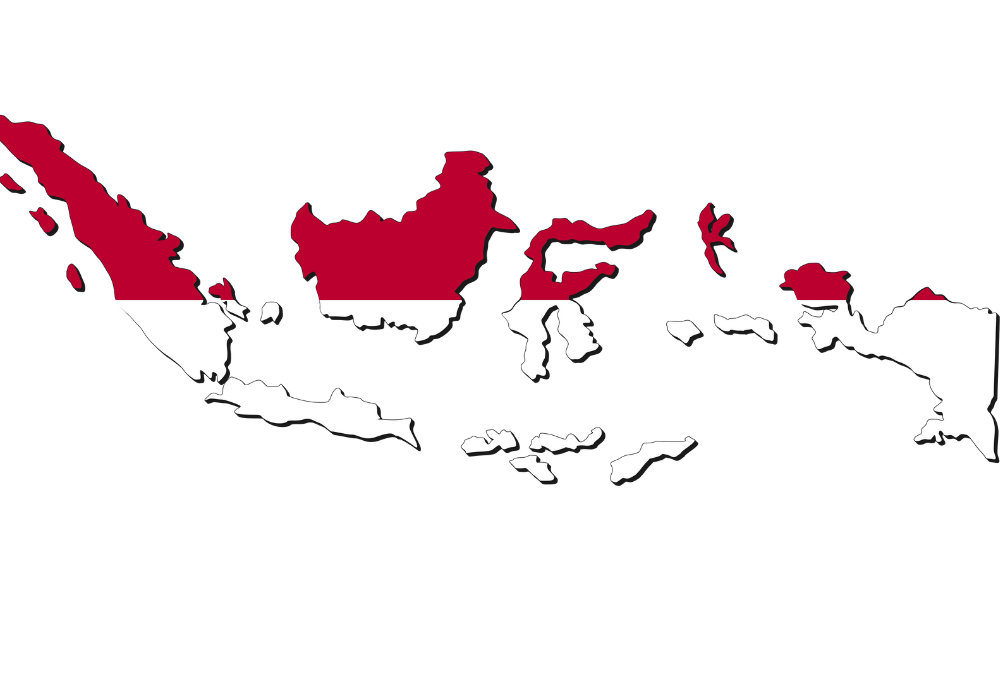SAKIP dan Ilusi Kinerja Pemerintah Daerah

Setiap tahun, Kementerian PAN-RB rutin mengumumkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Seperti lomba tahunan, pemerintah daerah berjejer menanti predikatnya: A, BB, atau B. Tidak jarang kepala daerah dengan bangga memamerkan sertifikat SAKIP di media sosial atau baliho besar di alun-alun kota. Namun, pertanyaan sederhana pun muncul: apakah nilai SAKIP tinggi selalu berarti kinerja pemerintahan yang baik dan dirasakan warga?
Oleh Eka Satialaksmana
Pemerintah Provinsi Banten adalah Salah satu entitas penilaian SAKIP yang tiap tahunnya diberika predikat oleh KemenPAN dan RB.
Tahun 2025 Provinsi Banten mendapat predikat B dengan nilai 69,31 poin hingga triwulan II tahun 2025. Sedangkan provinsi tetangganya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta berpredikat A. Bahkan Daerah Istimewa Yogyakarta meraih predikat AA.
Antara Nilai dan Realitas
SAKIP, secara konsep, adalah sistem manajemen kinerja pemerintah. Tujuannya mulia: agar setiap rupiah anggaran publik dapat diukur hasil dan manfaatnya. Sistem ini dirancang untuk memastikan birokrasi bekerja bukan sekadar menjalankan kegiatan, tapi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Namun praktiknua, banyak pemerintah daerah terjebak dalam orientasi nilai dan predikat, bukan pada substansi perubahan. Dokumen disusun dengan rapi, indikator kinerja diatur sedetail mungkin, tetapi pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa—lambat, tidak inovatif, dan sering tidak menyentuh akar persoalan warga.
SAKIP kemudian berubah fungsi: bukan sebagai alat pembelajaran organisasi, melainkan alat kosmetik birokrasi. Kepala daerah dan OPD berlomba-lomba mempercantik laporan agar nilainya tinggi, seolah-olah kinerja publik sudah paripurna. Padahal, di lapangan, dampak kebijakan kerap tidak terasa.
Budaya Nilai, Bukan Budaya Kinerja
Fenomena ini lahir dari kultur birokrasi yang masih sangat administratif. Banyak ASN menganggap SAKIP sebatas urusan dokumen tahunan, bukan refleksi strategis tentang efektivitas kebijakan.
Orientasi pada nilai juga diperkuat oleh tekanan simbolik dari pusat: KemenPAN-RB setiap tahun mengumumkan hasil evaluasi secara terbuka, lengkap dengan peringkat daerah. Maka, nilai “BB” menjadi trofi, bukan cermin pembelajaran.
Akibatnya, lahirlah kinerja semu — di atas kertas semua tampak baik, namun di lapangan, masyarakat tidak merasakan perubahan signifikan. Program dijalankan untuk memenuhi indikator, bukan untuk menjawab masalah publik. Inovasi sering terhambat karena takut keluar dari format yang bisa menurunkan nilai SAKIP.
Regulasi Sudah Kuat, Tapi Orientasinya Perlu Direformasi
Secara regulatif, SAKIP berdiri di atas landasan hukum yang kokoh. Mulai dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan anggaran berbasis kinerja, PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, hingga Perpres No. 29/2014 tentang SAKIP yang menjadi payung utama sistem ini.
KemenPAN-RB dan BPKP menjadi pembina dan evaluator, sementara Kemendagri memastikan integrasi dengan sistem perencanaan daerah.
Artinya, dari sisi aturan dan kelembagaan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki arsitektur akuntabilitas kinerja yang solid.
Masalahnya bukan pada “apa yang diatur”, melainkan bagaimana semangatnya diterjemahkan di lapangan.
Ketika SAKIP dijalankan sebagai ritual administratif, esensinya hilang. Evaluasi berubah jadi seremoni, bukan proses belajar.
Padahal, jika dijalankan dengan benar, SAKIP bisa menjadi instrumen yang sangat kuat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
Ia bisa menjadi kompas strategis yang memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program benar-benar terhubung. Tapi itu hanya terjadi jika kepala daerah dan birokratnya memiliki orientasi pada hasil, bukan pada sertifikat.
Mengubah Orientasi: Dari Penilaian ke Pembelajaran
Untuk menjaga relevansinya, SAKIP perlu direformasi secara filosofis dan teknis.
Pertama, orientasi harus bergeser dari penilaian menuju pembelajaran. Evaluasi tidak boleh berhenti pada skor atau predikat, tapi harus digunakan untuk menemukan solusi atas kegagalan kebijakan.
Kedua, birokrasi harus berani mengukur dampak (outcome), bukan hanya keluaran (output). Saat ini banyak indikator yang masih administratif: jumlah pelatihan, rapat, atau kegiatan. Padahal yang penting adalah: apakah pelatihan itu meningkatkan kapasitas ASN? Apakah program benar-benar memperbaiki kualitas hidup masyarakat?
Ketiga, partisipasi publik perlu diperkuat. Selama ini, evaluasi SAKIP lebih banyak dilakukan oleh pemerintah sendiri. Padahal, warga adalah pihak yang paling tahu apakah layanan publik sudah membaik atau belum. Survei kepuasan masyarakat, audit sosial, dan mekanisme umpan balik publik harus menjadi bagian dari sistem akuntabilitas kinerja.
Keempat, teknologi harus dimanfaatkan untuk memangkas beban administratif. Integrasi SAKIP dengan sistem perencanaan dan keuangan digital bisa mengurangi tumpukan dokumen dan mempercepat analisis data kinerja. Dengan begitu, ASN bisa lebih fokus berpikir strategis daripada sekadar menyiapkan bukti laporan.
Tanggung Jawab Moral dan Intelektual
Pertanyaan kuncinya: siapa yang paling bertanggung jawab memastikan SAKIP berdampak nyata?
Secara formal, tentu KemenPAN-RB sebagai perancang kebijakan nasional. Namun tanggung jawab moral dan intelektual terbesar sesungguhnya ada di kepala daerah dan Bappeda.
Merekalah yang tahu konteks lokal, yang berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat, dan yang seharusnya menerjemahkan semangat akuntabilitas menjadi tindakan konkret.
Tanpa komitmen pimpinan daerah, SAKIP hanya akan menjadi dokumen tahunan yang tidak hidup. Sebaliknya, ketika kepala daerah menjadikan SAKIP sebagai alat berpikir, bukan sekadar alat lapor, maka sistem ini bisa menjadi pendorong perubahan yang nyata.
Sebuah Refleksi
SAKIP masih dibutuhkan. Tanpa sistem akuntabilitas, birokrasi akan kembali bekerja tanpa arah dan ukuran.
Namun yang perlu diubah adalah jiwanya, dari sekadar alat penilaian menjadi alat pembelajaran.
“Selama nilai SAKIP menjadi tujuan, bukan hasil dari perubahan sistem kinerja, maka akuntabilitas hanya berhenti pada kertas, bukan pada kinerja.”
Jika pemerintah pusat dan daerah mau beranjak dari logika seremonial menuju logika pembelajaran, maka SAKIP bisa kembali pada rohnya: memastikan setiap kebijakan publik memberi hasil nyata bagi masyarakat.
Dan di situlah, nilai sejati akuntabilitas birokrasi bukan diukur dari predikat “A” atau “BB”, melainkan dari satu hal yang lebih penting, rasa percaya warga bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk mereka. (***)
Penulis adalah warga Banten tinggal di Serang