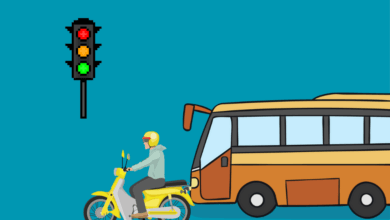Cinta yang Main-main

Aku lapar. Segera saja aku bergegas menuju rumah makan mie instan yang nikmat dan harganya sangat murah. Menurutku, uang yang harus dikeluarkan untuk membeli makanan tidak perlu banyak. Sederhana saja dalam membeli makanan. Rencananya, aku akan menabung uangku di bawah bantal untuk keperluan memikat seorang perempuan. Wajahku bisa dikatakan kurang rupawan jika disandingkan dengan Hamish Daud. Badanku tambun dan nihil otot. Aku juga masih enggan untuk dewasa. Kedewasaan adalah suatu hal yang merepotkan. Kedewasaan identik dengan keseimbangan. Seimbang antara bermain dan bekerja. Aku hanya ingin bermain. Saat aku bermain, hatiku merasa senang. Hati yang senang menghantarkanku menuju keabadian.
Seorang aku yang enggan dewasa apakah bisa merasakan indahnya jatuh cinta? Bolehkah aku bermain-main dalam cinta? Kata temanku cinta tanpa kedewasaan hanyalah nafsu belaka. Apakah tidak boleh jika cinta didasari oleh nafsu? Aku bertanya kepada dunia. Semoga dunia berkenan menjawabnya.
Sesampainya aku di rumah makan mie instan, aku segera memesan mie berkuah dengan es teh manis. Paket komplit untuk mengatasi amarah perut yang belum dinafkahi selama dua hari. Aku pelit dalam hal makanan. Aku lebih baik kelaparan daripada harus kehilangan kesempatan untuk beradu kasih dengan perempuan Jakarta. Kata-kata cinta sudah kulontarkan setiap hari. Bala bantuan kukirimkan saat dia sedang dilanda nelangsa. Telingaku siap sedia 24 jam untuk mendengarkan keluh kesahnya saat menjalani hidup sebagai mahasiswa baru. Tetapi, setelah aku melakukan analisa, ia belum tertarik kepadaku. Ia masih enggan mengakui bahwasannya aku ini adalah takdirnya. Suatu waktu, di rumah makan mie instan yang sama, aku pernah bertanya kepadanya via gawai. “Aku sedang berada di rumah makan mie instan, aku makan mie berkuah yang dilengkapi dengan sawi dan telur rebus. Untuk mengatasi tenggorokan kering aku membeli es teh manis. Kalau kamu sedang makan apa sekarang?”, tanyaku kepadanya.
“Aku juga sedang makan mie berkuah dan juga dilengkapi dengan sawi dan telur rebus. Aku juga membuat teh manis tanpa es. Aku dilarang menggunakan es.”, terdengar suara berisik yang dihasilkan mulutnya ketika bergelut dengan mie instan.
“Wah, menu yang kita makan sama. Mungkin ini adalah alasan kita untuk berjodoh. Maukah kau menjadi jawaban dari doaku? Kamu harus tahu, aku selalu berdoa agar tuhan menakdirkanku untuk selalu bersama denganmu. Bahkan aku pun berdoa agar kita meregang nyawa bersama. Sekali lagi aku ingin bertanya, maukah kamu menjadi istriku?”, entah mengapa empat kata bodoh itu terucap dari mulutku. Tanpa ancang-ancang, ia pasti akan terkejut dan juga akan memuntahkan seluruh mie yang ada di dalam mulutnya.
“Untuk saat ini, berat sekali kukatakan aku belum ingin menjadi istrimu. Alasan yang kau lontarkan barusan sungguh kekanak-kanakan. Kamu hanya memikirkan tentang kenikmatan diri yang akan kamu terima setelah ritus pernikahan kita berlangsung. Aktivitas malam pertama sebagai pasangan suami-istri adalah cita-citamu sedari kecil. Kamu masih belum memiliki rancangan bagaimana mempertahankan stabilitas keharmonisan keluarga kecil kita nanti. Jiwamu masih dirongrong nafsu. Aku takut ketika ada perempuan lain yang lebih aduhai daripada aku, nafsu kamu akan meluap-luap. Kemaluanmu yang lugu itu akan memiliki pikiran untuk menusuk kemaluan perempuan lain. Aku sangat tersinggung ketika kamu berbicara alasan tuhan mengabulkan doamu itu hanya karena persamaan menu makan kita. Menurutku itu sangat sepele dan tidak masuk di akal. Untuk saat ini, aku belum bisa mengatakan ‘iya’. Tapi, aku akan sabar menunggumu untuk memperbaiki segala yang rusak pada dirimu. Mudah-mudahan kamu tidak marah dan segera untuk memperbaiki diri. Semua akan “iya” pada waktunya.”, begitulah tanggapan perempuan Jakarta ketika aku mengatakan sebuah kata-kata wajib sebelum menikah.
Aku langsung membanting gawaiku dengan penuh amarah. Tidak pernah aku diremehkan seperti ini. Seorang perempuan berani mengklaim diriku sebagai laki-laki maniak seks. Aku juga dianggapnya akan mengacuhkan keluarga dan berfokus untuk memuaskan nafsu seksku. Ini adalah bentuk penghinaan. Ringan sekali mulut dia untuk menghinaku. Seperti tidak pernah belajar agama. Mungkin aku perlu memberi tahunya kalau aku sudah belajar agama selama 12 tahun tanpa henti. Agama kujadikan tameng pelindung diri dari segala dosa besar. Semenjak aku dekat dengannya, aku tidak pernah sekalipun mengelus pipinya yang mulus. Aku tidak pernah menggegam tangannya. Dan aku pun tidak pernah menyentuh bibirnya dengan bibirku. Aku hanya berbagi informasi mengenai kehidupan pribadiku dan ia juga berbagi informasi tentang kehidupan pribadinya. Tidak lebih dari itu. Bahkan, aku tidak ada hasrat seksual kepadanya. Aku memuliakan dirinya. Pendekatan batin lebih aku tekankan daripada pendekatan biologis. Keluarga yang abadi keharmonisannya karena sebelum menikah sudah membangun hubungan batin yang sempurna. Tidak dibangun dengan hubungan biologis. Aku sudah paham sepenuhnya dan dia seharusnya ia juga paham. Entahlah. Mungkin ini hanya soal waktu. Semua akan menikah pada waktunya.
Setelah mengingat peristiwa menyebalkan itu, entah mengapa aku ingin merusak barang yang ada di rumah makan ini. Rasanya ingin sekali membanting mangkuk beserta gelas hingga pecah berkeping-keping. Setelah itu, aku berteriak sumpah serapah agar seantero rumah makan bisa merasakan kemarahan yang merengkuh jiwaku. Aku ini penganut sosialisme sejati. Semua orang harus merasakan apa yang aku rasa. Presiden pun harus merasakan penderitaanku. Aku pernah berkunjung ke istana negara untuk menghantarkan rasa deritaku yang tak kunjung usai. Aku datang seorang diri dan bermaksud untuk mencari perkara dengan presiden. Kalau bisa aku ingin bertarung melawan presiden hingga ia babak belur. Akan sangat lucu jika presiden berlutut memohon ampunanku dan dibalut dengan wajah lemas yang jenaka. Aku datang seorang diri dan membawa karton bertuliskan kata-kata sumpah serapah. Aku datang dengan tangan kosong. Tetangga-tetanggaku pernah berkata kalau tinjuanku bisa membuat seseorang menderita seketika. Entah bibir memuntahkan darah, pipi yang biru lebam, gigi-gigi yang tanggal, sampai napas tersengal-sengal seperti ingin menemui ajal.
Baru saja sampai di depan gerbang istana yang jumawa, aku ditangkap oleh dua aparat bajingan. Kedua aparat itu menahanku dan menanyakan maksud dan tujuan mengapa datang ke istana negara. Aku jawab dengan rileks tanpa adanya rasa takut. Aku bilang bahwa aku ingin menyiksa presiden agar ia bisa merasakan penderitaan hidupku. Seorang presiden harus mau menderita bersama rakyat, bahagia bersama rakyat, dan kalau bisa hidup serumah bersama rakyat. Presiden tidak boleh merasa nikmat sendiri. Karena kenikmatan yang ia dapat berasal dari tuhan melalui perantara rakyat yang patuh membayar pajak sebelum jatuh tempo. Awalnya, kedua aparat bajingan itu bingung dan mendadak dungu. Mereka juga tidak sadar bahwa aku sudah lepas ada didepannya. Dalam keadaan dungu, aku langsung menusuk kedua aparat bajingan menggunakan bambu runcingku. Hanya dua kali tusukkan. Sedikit. Yang penting mereka bisa segera menemui alam kubur. Tidak banyak orang yang melihat kejadian itu. Aku menusuk mereka saat dunia sudah gelap. Rekan-rekannya sedang tidur. Kesempatan untuk menyiksa presiden terbentang luas di pelupuk mata. Dengan cekatan, aku memanjat pagar istana. Memanjat bukan hal yang asing bagiku. Sejak kecil aku selalu memanjat. Alasannya aku punya teman khayalan di atas pohon. Setiap waktu teman khayalanku bertengger di salah satu ranting pohon. Mengobrol dengannya sungguh asyik. Banyak nilai-nilai filosofi yang terselip di setiap untaian katanya. Aku semakin terkagum-kagum dan bahkan siap untuk menyembahnya. Berlebihan sekali aku.
Aku mendarat secara sempurna. Istana terlihat sepi. Para penjaga sudah bosan untuk menjaga stabilitas istana. Mereka lebih memilih untuk tidur dan merapikan mimpi-mimpi yang tercecer. Aku memanfaatkan kesempatan suasana sepi ini untuk segera masuk ke dalam istana. Bayangan muka presiden yang biru lebam sudah memenuhi benakku. Aku sudah tidak sabar. Aku berjalan cepat, pandangan lurus menghadap daun pintu istana, kedua tangan sudah mengepal kokoh, dan yang paling aku benci ialah, jantungku berdebar kencang sekali. Adrenalin semakin terpacu. Sorak sorai yang dilakukan organ tubuh semakin meyakinkan diriku bahwa rencana yang kulakukan ini ada benarnya. Semakin dekatku dengan daun pintu. Kakiku siap untuk mendobrak secara tiba-tiba. Inilah saatnya. Dihadapanku sudah berdiri sombong daun pintu istana. Kutenangkan diriku. Aku berdoa terlebih dahulu. Kutundukan kepalaku. Selesai berdoa, aku mulai melakukan ancang-ancang. 1…. 2…. 3…. Dor!. Shotgun menyalak. Aku rubuh. Salah satu penjaga berhasil merobek pahaku dengan shotgun. Aku gagal. Aku dibawa ke rumah sakit untuk dipulihkan sebelum mendekam di penjara. Secara resmi, aku adalah narapidana dengan tuduhan mengancam nyawa presiden. Aku didakwa 3 tahun penjara. Apakah itu sebuah masalah bagiku? Bagiku tidak. Mengapa? Tidak tahu.
Aku adalah mantan narapidana yang berkiat untuk menggapai cinta seorang santriwati. Teman-temanku sering tertawa terkencing-kencing mendengarkan wacanaku ini. Mustahil santriwati menaruh perhatian kepada seorang mantan narapidana. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Aku mempunyai kuasa untuk merubah kemustahilan dunia. Aku bisa saja merebut dan menikahi istri presiden. Kemustahilan adalah mustahil bagiku. Lihat saja nanti, aku akan menikah dengan santriwati dan mempunyai keturunan yang melimpah. Hingga bumi mengeluh tidak sanggup menampung seluruh keturunanku. Semua ras di bumi akan musnah dan digantikan oleh ras yang kuciptakan sendiri.
Cita-citaku sangat masuk akal. Semua cita-cita akan dicapai jika memiliki tekad yang kuat untuk mencapainya. Kalau hanya bermalas-malasan cita-cita serendah apapun tidak mungkin tercapai. Mau cita-citamu ingin menikah dengan seekor babi juga tidak akan tercapai. Kamu harus memulai langkah awal untuk menghantarkanmu dalam meraih cita-cita. Jangan terlalu banyak berpikir. Berpikir hanya akan membuatmu menjadi manusia yang malas. Sebelum tidur berpikir, sebelum makan berpikir, sedang buang air besar berpikir, sedang berzina berpikir, sedang mengeluarkan paksa sperma berpikir. Berpikir itu candu. Berpikir melemahkan mental kalian. Lakukan saja. Jika ada yang mengolokmu, tinju. Jika masih saja mengolok, hantam kedua pelirnya. Jika masih saja mengolokmu walau tergagap-gagap, ledakan dia. Ia hilang dan tidak mengolokmu kembali.
Memang terdengar kejam. Aku tidak peduli. Kekejaman terkadang dibutuhkan untuk menguntungkan aku. Manusia akan berhenti berkicau saat mereka mati. Mulut bajingannya sudah mampus dilalap maut. Mungkin keluarganya, teman dekatnya, istrinya, cucu-cucunya, selingkuhannya, lontenya, pemasok narkobanya, teman judinya, orang yang pernah dihutanginya, dan teman mabuknya akan menangis kehilangan. Mereka akan berbondong-bondong menuju ke pemakamannya untuk melepas kepergian sang pengolok. Kidung sedih dinyanyikan. Air mata dan ingus mereka jatuh bersama-sama. Aroma ingus menyeruak seantero makam. Karena tak tahan dengan aroma tersebut, Mereka akhirnya muntah-muntah. Anak-anak kecil muntah di batu nisan sang pengolok. Tempat pemakaman berubah fungsi menjadi tempat penampungan muntah. Kesimpulannya, sang pengolok memiliki derajat yang sama dengan muntahan orang-orang yang hadir di pemakamannya.
Aku tertawa. Tertawa dengan keras. Suasana sedih adalah kesempatan bagiku untuk tertawa. Aku adalah manusia yang berbeda. Rasku dengan ras manusia yang ada di bumi berbeda. Caraku menyikapi sebuah perstiwa pun berbeda. Untuk menambah keriaan di hari sedih tersebut kuputar lagu “Ha Ha You’re Dead” milik Green Day. Dia mati. Lelucon sudah berakhir. Dia bajingan. Selamat menikmati palu malaikat. Selamat menderita ria. Selamat mencicipi kobaran api neraka.
“Kamu sudah gila. Penjara merubah pola pikirmu. Apa yang kamu lakukan sesaat mendekam di penjara? Apakah kamu membaca buku tentang anarkisme? Atau kamu dipukuli setiap saat oleh teman-temanmu? Mimpimu itu diluar nalar dan keji. Agama kita tidak memperkenankan kita untuk bermimpi seperti itu. Jika kau ingin menikahiku, cobalah untuk memperbaiki mimpimu. Bermimpi yang benar. Bermimpi yang sama dengan mimpi orang lain. Aku sarankan, kamu segera untuk tidur. Perbaiki otakmu. Perbaiki akhlakmu. Niscaya, mimpimu akan baik”, ucap sang santriwati ketika mendengar keseluruhan ceritaku.
“Siapa kamu mengatur aku dalam bermimpi? Mimpimu dan mimpiku berbeda. Mimpimu terlalu rendah untuk dimimpikan. Kamu tidak patuh kepada nasehat Soekarno. Mimpi yang aku mimpikan adalah mimpi yang matang. Sudah aku teliti mimpiku dengan metode main-main. Tidak ada mimpi yang tidak logis. Keseriusanmu yang membuat mimpi menjadi tidak logis. Ayolah, sayang, jangan serius. Habiskan hidupmu dengan main-main. Hidup tidak perlu dibuat repot. Main-main yang banyak. Ingat itu”
Tiba-tiba, sang santriwati mengeluarkan sebilah golok. Ia mengacungkannya kepadaku. Ia mengancamku. Ia hendak menghujam jantungku dengan golok itu. Ia hendak mengirimku ke liang lahat. Aku tidak gentar. Aku busungkan dadaku agar memudahkan ia saat membunuhku. Bukankah mempermudah perkara orang lain maka tuhan akan memudahkan perkara kita? Aku memikirkannya. Oh, tidak. Aku berpikir. Aku tidak mau berpikir. Aku tidak mau ada. Aku hanya ingin tidak ada. Keadaan bisa mendatangkan masalah. Bunuh aku, perempuan. Bunuh aku.
Dor! Suara tembakan tetiba menggema. Sang santriwati mati. Ditembak polisi. Mengapa polisi menembak santriwati? Apakah dia jahat? Aku tanyakan kepada polisi itu.
“Mengapa kau menembak kekasihku?”
Dor! Dor! Dor!. Polisi itu menembakku. Aku selesai. Cerita ini pun selesai.
![]()